Toleransi, adalah kata yang sangat mudah diucapkan tetapi susah dipraktikkan. Toleransi yang dimaksud termasuk ketika memilih bahasa atau jargon dalam berkomunikasi antar agama. Agaknya persepsi diri sebagai mayoritas, sebagai yang terbanyak, terbesar dan terkuat, melahirkan arogansi terhadap minoritas yang dipersepsikan sedikit, kecil dan lemah. Ini adalah fakta dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Padahal, dalam kondisi multi agama seperti di negara kita, praktik toleransi antar agama mutlak dibutuhkan. Toleransi tersebut sepatutnya terwujud dalam berbahasa. Prinsip saling menghargai dan kesantunan berbahasa antar agama amat memungkinkan masyarakat untuk menaburkan bibit kedamaian, menghembuskan kesejukan di tengah kecamuk amarah yang membadai akibat perbedaan prinsip dan keyakinan hidup. Namun, agaknya bahasa-bahasa yang digunakan dalam kehidupan keberagamaan belum seperti itu, sehingga belum mampu membangun tatanan nilai hidup yang jauh lebih beradab dan berbudaya. Yang sering mencuat ke permukaan justru bahasa-bahasa arogan yang mengancam kerukunan dan semangat perdamaian. Adanya istilah: Agama Langit – Agama Bumi adalah salah satu contoh arogansi berbahasa dalam komunikasi antar agama. Penggolongan ini paling disukai oleh pemeluk Agama Langit (Islam, Kristen, dan Yahudi) radikal karena secara tidak langsung termaknai sebagai tinggi – rendah. Yang tinggi merasa pantas untuk menginjak atau menerabas yang rendah. Yang tinggi merasa ada di pihak Tuhan dan yang lain berseberangan dengan Tuhan sehingga perlu diselamatkan.
Demikianlah, prinsip saling menghargai dan kesantunan berbahasa makin jauh terjerembap dalam semangat primordialisme semu, sehingga tak sedikit orang yang demikian gampang “mengkafirkan” atau “menyesatkan” pihak lain yang tidak sepaham dan satu keyakinan. Yang memprihatinkan, sekarang komunikasi telah tergantikan oleh benda-benda pembawa petaka. Pedang dan pentungan, bahkan bom tak jarang digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti pihak lain di ruang publik demi memperoleh pembenaran terhadap prinsip dan keyakinan yang dianutnya. Siapa pun yang masih mempunyai nurani tentu akan sedih ketika sentimen keagamaan di Indonesia dijadikan sebagai dalih untuk menaburkan kebencian kepada pihak lain yang berbeda agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan mulai tampak goyah dan bergetar akibat makin maraknya perilaku dan sentimen keagamaan yang sama sekali jauh dari semangat toleransi. Terlepas apa pun motifnya, jalan kekerasan mana pun yang ditempuh dipastikan tak akan pernah sanggup menyelesaikan masalah. Sungguh, ternyata berurusan dengan sesama manusia jauh lebih rumit ketimbang berurusan dengan Tuhan yang tak pernah mengajarkan paham dan bahasa kekerasan kepada hambaNya. Kembali kepada persoalan Agama Langit – Agama Bumi. Saya pikir ini adalah dikotomi yang paling kontras dan tendensius. Sebenarnya sudah usang, tapi sampai sekarang masih banyak yang berminat menggunakannya. Saya teringat, beberapa waktu yang lalu, di sebuah grup diskusi internet, terjadi diskusi yang kemudian berubah menjadi debat sengit antara seorang mahasiswa Hindu dengan beberapa orang yang mengaku jebolan pesantren. Debat dipicu oleh status pancingan yang menyatakan bahwa Agama Hindu itu adalah Agama Bumi atau Agama Budaya, jadi bukan wahyu Tuhan. Sebagai Agama Bumi, maka dikatakan Hindu itu dibuat oleh manusia seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sangat berbeda dengan Agama Islam dan Kristen yang merupakan Agama Langit yang dikatakan diwahyukan oleh Allah. Agama Langit khususnya Islam adalah agama penyempurna Agama Langit terdahulu. Tidak menunggu lama, mahasiswa Hindu tersebut membuat balasan dengan mengatakan Islam itu mengajarkan kekerasan karena menghalalkan untuk membunuh kafir, menghalalkan perbudakan, Islam juga mencetak teroris, dan seterusnya. Sebuah komentar balasan yang emosional dan dangkal. Emosional karena menyerempet dan menghubungkan atau mengidentikkan Islam dengan kekerasan dan teroris, dangkal karena tanpa wawasan yang cukup tentang Islam. Maklumlah karena dia adalah seorang mahasiswa baru. Demikianlah, ratusan komentar diposkan hanya dalam waktu tiga jam. Rupanya, status sontoloyo itu memecahkan rekor komentar terbanyak dalam sehari, saya lihat 1.132 komentar. Bayangkan betapa serunya! Tapi diskusi tersebut sepertinya tidak memberi manfaat apa-apa. Semua mengumbar argumentasi yang emosional dan kekanak-kanakan. Di antara sekian banyak komentar, sepertinya tidak ada yang smart, elegan, dan mencerminkan intelektualitas. Saya yang sesekali mengamati diskusi itu akhirnya menjadi gatal dan tergoda untuk berkomentar, walau sebenarnya hanya sekedar bercanda dengan si pembuat status. Saya menulis: “Lebih baik Agama Bumi dari pada Agama Langit. Agama Bumi itu artinya membumi, bermanfaat bagi manusia di bumi. Karena kita masih hidup dan tinggal di bumi, belum di langit. Dan setelah mati pun kalau belum memungkinkan dibakar, maka jazad saya akan dikebumikan, bukan dikelangitkan he he he. Dan begitu juga jika disebut Agama Budaya, Hindu itu membuat umatnya hidup beradab dan berbudaya. Hindu tidak membenarkan perilaku barbar. Dalam ajaran Hindu ada Ahimsa (tidak menyakiti makhluk lain) yang merupakan dharma tertinggi”. Ternyata kelakar saya tersebut membuat mereka bungkam. Demikianlah faktanya, selalu saja ada yang semena-mena dalam kedudukan mayoritasnya dengan menginjak-injak minoritas. Salah satu cara protes yang dewasa adalah dengan tulisan, baik artikel maupun buku seperti yang sudah dilakukan melalui buku ini. Buku “Mendebat Agama Langit” ini menyajikan fakta dan realitas, khususnya tentang arogansi pemeluk Agama Langit terhadap pemeluk Agama Bumi. Inilah cara yang menurut saya lebih smart, elegan dan intelek dalam berargumen. Buku dibalas dengan buku (bukan dengan pentungan atau pedang), sehingga kalau pun ada konflik, itu hanya konflik argumentasi yang dengan sendirinya diadili oleh fakta dan realita. Dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, konflik argumentasi tidak akan menjadi konflik fisik yang horisontal. Semoga buku ini menjadi sebuah instrumen untuk memutus arogansi dalam dikotomi ngawur Agama Langit – Agama Bumi, sehingga tercipta kesadaran untuk saling menghargai, mengakui kesejajaran dalam kehidupan beragama. Sebagai penutup, penggalan syair berikut cukup relevan untuk direnungkan;
“Kau seperti bis kota atau truk gandengan.
Mentang mentang paling besar klakson sembarangan.
Aku seperti bemo atau sandal jepit.
Tubuhku kecil mungil biasa terjepit.
Kau seperti buaya atau dinosaurus.
Mentang-mentang menakutkan makan sembarangan.
Aku seperti cicak atau kadal buntung.
Tubuhku kecil merengit sulit dapat untung.
Mengapa besar selalu menang?
Bebas berbuat sewenang wenang.
Mengapa kecil selalu tersingkir?
Harus mengalah dan menyingkir.
Apa bedanya besar dan kecil?
Semua itu hanya sebutan.
Ya walau didalam kehidupan, kenyataannya harus ada besar dan kecil”.
(Dari lagu: Besar dan Kecil oleh Iwan Fals).
Page Paradev.

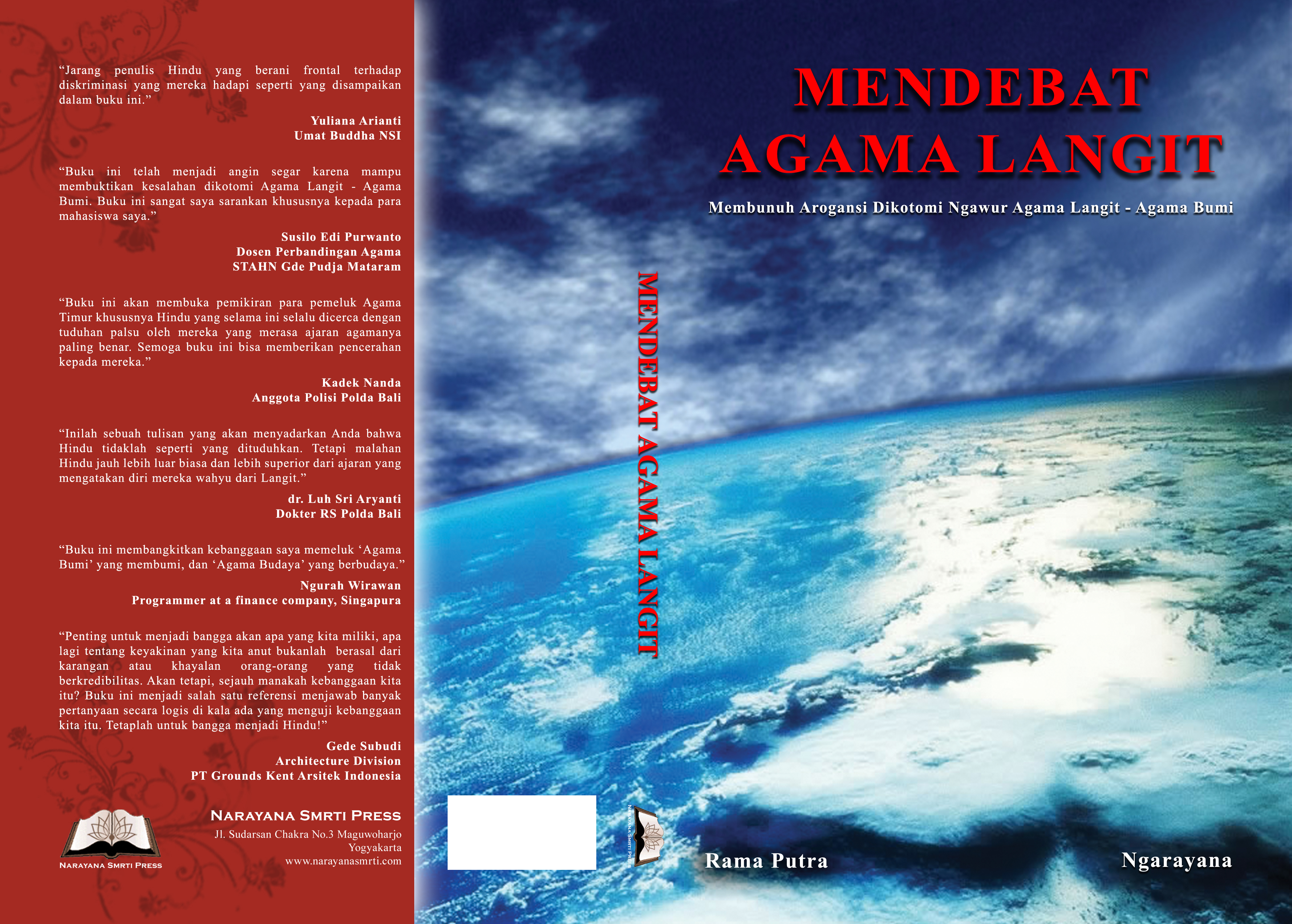
Thanks!. Tulisan yang perfect dan mencerahkan. Saya orang Kristen tetapi saya berfikir bukan soal kristennya. Karena, Orang lebih membelah lembaga agama daripada ajarannya. Teks tidak dapat dirubah tetapi konteksnya harus dirubah. Faktanya kita ada dibumi, kita belum kesurga karena semua kebutuhan ada dibumi dan semua itu ada dalam kewenangan kita sbg manusia untuk mengaturnya. segala peraturan dibuat oleh manusia dengan pertimbangan yang sehat. Untuk kebaikan dan kebutuhan seluruh umat mc.